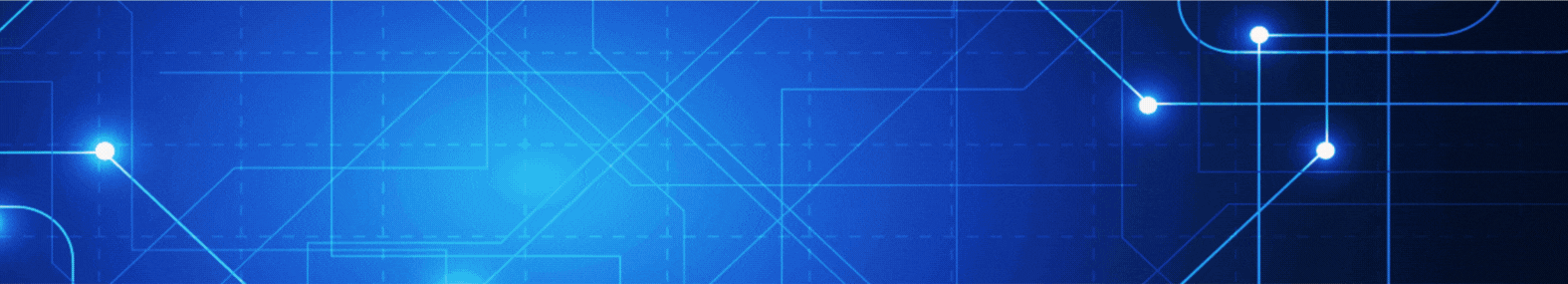Di tengah saya menyimak siaran langsung sidang PHPU Mahakam Ulu yang ternyata masih berlanjut ke tahap pembuktian Kamis (26/6/2025), perhatian saya langsung teralih ke sidang lain yang tak kalah penting.
Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan nomor perkara 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilu lima kotak.
MK mengabulkan permohonan Perludem. MK menyatakan sistem pemilu serentak sebagai inkonstitusional bersyarat, dan memerintahkan agar pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah mulai 2029.
Ini bukan keputusan kecil. Kita tahu, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 disusun dengan semangat menyatukan semua kontestasi dalam satu hari pemilihan. Lima kotak, satu momentum, satu efisiensi. Alasannya jelas. Menekan biaya, menyederhanakan logistik, dan menguatkan kepemimpinan politik yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.
Tapi arah itu kini dibalik. MK menilai keserentakan justru membebani pemilih, melemahkan partai politik, dan membuat isu lokal tenggelam dalam riuh kampanye nasional. Maka, mulai 2029, pemilu akan dipisah: nasional lebih dulu, daerah dua tahun kemudian.
MK menyatakan sistem pemilu serentak lima kotak—Presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota—adalah inkonstitusional secara bersyarat. Ke depan, pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisah pelaksanaannya. Pemilu untuk Presiden, DPR, dan DPD akan digelar lebih dulu. Dua hingga dua setengah tahun kemudian, barulah pemilu daerah digelar, untuk memilih kepala daerah dan DPRD di semua tingkatan.
Alasannya tampak rasional. Tapi di balik itu, ada satu pertanyaan besar yang tidak dibahas MK dan harus dijawab pemerintah maupun DPR: bagaimana nasib masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024?
Kalau pemilu nasional digelar 2029, logikanya pemilu daerah digelar 2031. Otomatis, masa jabatan DPRD akan molor menjadi tujuh tahun. Lalu, dasar konstitusionalnya apa? Rakyat memilih mereka untuk lima tahun.

Pasal 22E UUD 1945 menyatakan jelas: pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Kalau diperpanjang lewat revisi UU, itu bukan reformasi. Itu pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
Alternatifnya, masa jabatan justru dipotong demi menyesuaikan jadwal baru. Tapi ini juga absurd. Rakyat memilih untuk lima tahun, bukan tiga tahun. Siapa yang berhak memangkas waktu pengabdian yang dipilih langsung jutaan suara?
Jujur saja, kita sedang berjalan menuju ketidakpastian hukum. Pemerintah dan DPR memang bisa merevisi UU Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah. Tapi jangan lupa: tidak ada satu pun pasal yang membolehkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD tanpa pemilu. DPRD bukan kepala daerah. Tidak ada mekanisme penjabat DPRD. Dan kalau pun dipaksakan, itu artinya kita menciptakan kekacauan baru dalam sistem perwakilan.
Kepada wartawan, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menyebut DPR akan mengkaji revisi UU secara mendalam. “Kemungkinan besar DPRD akan bertambah masa jabatan sekitar dua tahun,” katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga mengatakan hal serupa. Pemerintah akan merespons lewat revisi undang-undang, tapi belum punya rumusan jelas. “Eksekusinya masih akan dipelajari secara detail,” ucapnya.
Sementara itu, ruang publik sudah lebih dulu bereaksi. Video amar putusan MK ramai dibagikan di TikTok. Tagar #PemiluPisah dan #Jeda2Tahun naik jadi tren. Komentar masyarakat tak main-main: “DPRD dapat bonus dua tahun? Itu bukan demokrasi. Itu akal-akalan!”
Pandangan pengamat pun bermunculan. Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, menyebut pemisahan pemilu memang membuat proses lebih tertata dan beban kerja penyelenggara lebih ringan. Tapi ia juga mengingatkan soal beban fiskal yang membengkak, potensi kejenuhan pemilih, hingga suburnya praktik “lompat panggung” politik antar pemilu.
Jika tidak dikelola dengan aturan ketat dan transparan, demokrasi bisa terjebak pada pola coba-coba dan kepentingan jangka pendek.
Kita tidak sedang mempermasalahkan semangat perubahan yang dibawa putusan MK. Putusan ini baru diketuk, dan wajar jika pemerintah serta DPR belum langsung punya jawaban utuh. Tapi justru karena itulah, pembahasan lanjutan menjadi krusial. Dan sebaiknya dimulai sejak sekarang, terbuka, serta melibatkan suara publik.
Untuk Kaltim, percakapan ini juga sudah mengemuka ke mana-mana. Di grup WhatsApp, di linimasa media sosial, bahkan di TikTok. Sudah ada yang menyebarkan bagan jadwal pemilu 2029 dan 2031, lengkap dengan asumsi bahwa masa jabatan DPRD akan diperpanjang sampai tujuh tahun.
Pertanyaan pun bermunculan. Benarkah akan diperpanjang? Dasarnya apa? Apa berlaku nasional atau hanya di daerah tertentu? Semua bertanya karena publik tak ingin hanya menonton saat arah demokrasi ditentukan dari atas meja. Apalagi Kaltim bukan wilayah biasa.
Provinsi ini sedang menjadi panggung utama pembangunan nasional. Di sini, Ibu Kota Nusantara dibangun. Di sini juga, DPRD punya peran penting: mengawal anggaran, menjaga keseimbangan pembangunan, dan mewakili suara warga dari pesisir hingga perbatasan.
Kalau masa jabatan mereka akan diperpanjang atau disesuaikan, itu bukan urusan administratif semata. Itu soal mandat. Dan mandat publik tidak bisa digeser begitu saja tanpa penjelasan.
Karena itu, pascaputusan MK ini sebaiknya tak dibiarkan mengambang. Warga berharap ada kejelasan sejak awal, agar tak muncul tafsir liar, polemik berkepanjangan, atau, yang paling dikhawatirkan, kekacauan politik di daerah.
Kaltim butuh kepastian. Bukan sekadar agar roda pemerintahan tetap jalan, tapi agar kepercayaan publik pada proses demokrasi tetap utuh. Jangan sampai ketidaksiapan pusat menciptakan masalah baru di daerah. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.