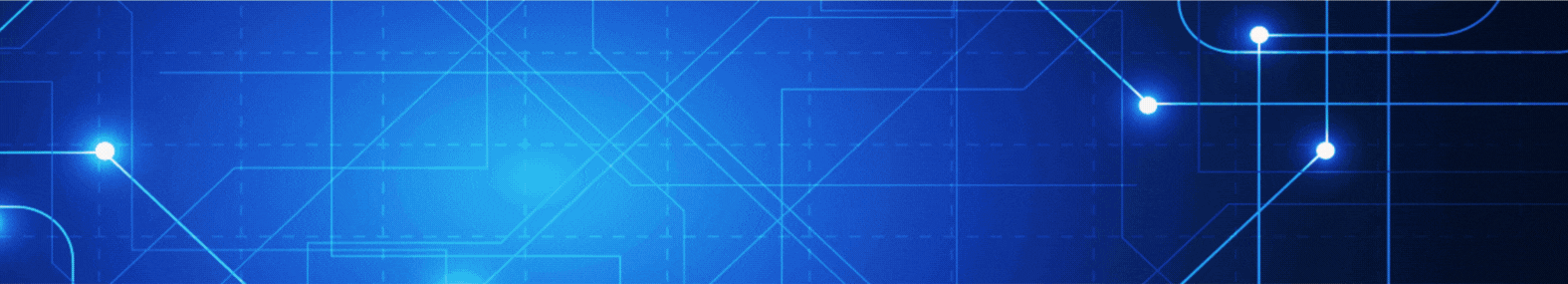Tiba-tiba kolega saya, Komisioner KPU Bontang Acis Maidy Muspa, mengirimkan tautan YouTube. “Ini tadi dibahas, Pak. Bisa ditonton lah,” katanya dalam pesan singkat.
Link itu berisi siaran ulang diskusi publik yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem Pemilu serentak, Jumat (27/6/2025).
Saya menduga, link ini dikirimkan setelah ia membaca ulasan saya sebelumnya soal implikasi putusan MK terhadap masa jabatan anggota DPRD. Dan benar saja. Isi diskusinya padat dan strategis. Bukan sekadar ruang akademik, tapi ajakan untuk memikirkan ulang seluruh desain Pemilu ke depan. Terutama oleh mereka yang selama ini merasa tak tersentuh reformasi elektoral.
Putusan MK sudah diketuk. Format pemilu lima kotak resmi ditinggalkan. Tapi, siapa yang akan memastikan transisi ini berjalan rapi dan konstitusional?
Saya tonton jalannya diskusi dari awal. Ini bukan semata urusan para ahli, tapi momentum krusial yang seharusnya menggugah partai politik, penyelenggara pemilu, pembentuk UU, dan publik luas.

Fadli Ramadhanil, Peneliti Senior dan Koordinator Divisi Hukum Perludem, membuka dengan penegasan yang langsung mengarah ke inti masalah. “Kita sudah dua kali mengalami Pemilu serentak lima kotak. Capek semua. Pemilih bingung, partai kelelahan, penyelenggara kewalahan,” ujarnya.
Menurut Fadli, sistem ini sudah membebani semua pihak, dan tak lagi relevan dengan semangat pelembagaan demokrasi.
Ia juga menyoroti bahwa ketidaksiapan partai politik untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi sepanjang waktu memperlihatkan kelemahan struktural. “Kalau semua pemilu ditumpuk dalam satu tahun, partai hanya bekerja lima tahunan. Itu bukan pelembagaan, itu pragmatisme,” tegasnya.
Heroik Pratama, Peneliti Senior Perludem, memberikan peringatan tentang implikasi teknis di lapangan. “KPU dan Bawaslu daerah akan habis masa jabatannya di 2027. Kalau Pemilu lokal dilaksanakan 2031, siapa yang bekerja mengelola tahapan? Harus ada rekrutmen ulang dengan masa tugas yang disesuaikan,” katanya.
Ia juga menyentil legitimasi politik. “Pj (Penjabat Red.) itu bukan solusi ideal. Kita sudah lihat sendiri polemiknya di Pilkada 2024. Kalau perlu diperpanjang masa jabatan, harus dengan dasar konstitusional yang jelas. Jangan dibiarkan menggantung,” sebutnya.
Sejumlah pembicara dalam diskusi juga menyinggung kemungkinan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai opsi transisi, asalkan ditempuh melalui revisi undang-undang yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Opsi ini dinilai lebih realistis dibanding membiarkan kekosongan kursi legislatif atau merancang skema baru yang belum teruji.
Namun, pandangan kritis juga tak sedikit. Salah satunya datang dari Charles Simabura, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, yang menjadi suara paling keras soal kepastian hukum. “DPR dan Pemerintah terlalu nyaman menunda. MK akhirnya mengambil alih karena pembentuk UU tak bergerak. Tapi ingat, memperpanjang masa jabatan DPRD itu tak punya dasar. DPRD itu lembaga kolektif, tidak bisa ditunjuk penjabat seperti kepala daerah,” tegasnya.
Charles juga mengingatkan bahwa jika Pemilu lokal dilaksanakan 2,5 tahun setelah Pemilu nasional, maka akan muncul ruang kekosongan kekuasaan. “Kita butuh kejelasan, bukan spekulasi. Jangan tunggu sampai 2028 baru panik. Undang-undang transisi harus dibahas sekarang. Dan ini tak boleh dibungkus dalam wacana elite saja, harus terbuka dan menyertakan publik.”
Ia bahkan mengusulkan agar pemetaan ulang norma hukum dilakukan melalui kodifikasi dua kitab pemilu: satu untuk pemilu nasional, satu untuk pemilu lokal. “Karena pola kerja, koalisi, logistik, bahkan rekrutmen caleg dan kampanye akan sangat berbeda. Kita butuh sistem yang mampu mengantisipasi bukan hanya tanggal, tapi juga dinamika politiknya,” tuturnya.
Khoirunnisa Nur Agustyani, Direktur Eksekutif Perludem, menekankan bahwa kita butuh perubahan cara pandang terhadap sistem pemilu. “Ini bukan hanya soal teknis hari pencoblosan. Tapi bagaimana kita memahami pemilu sebagai proses berjenjang antara pusat dan daerah. Ada kebutuhan untuk memisahkan secara tegas antara Pemilu nasional dan lokal, baik dari segi desain maupun tujuannya,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun struktur politik yang memungkinkan kaderisasi berkelanjutan. “Jangan sampai Pemilu hanya jadi pesta lima tahunan tanpa kesinambungan. Ini saatnya menyusun ulang peta demokrasi kita secara lebih matang dan berjenjang.”
Hadar Nafis Gumay, Pendiri Netgrit dan mantan Komisioner KPU RI, menambahkan bahwa pekerjaan besar justru baru dimulai. “Putusan MK ini baru pintu masuk. Reformulasi desain penyelenggaraan pemilu harus segera dimulai. Kalau tidak, kita hanya memindahkan kekacauan dari satu tahun ke tahun lain,” sebutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masa jabatan penyelenggara pemilu di pusat dan daerah harus selaras dengan tahapan baru, agar tidak ada benturan operasional.
Semua pernyataan itu membawa kita pada satu titik kesimpulan: keputusan sudah ada, tapi desain pelaksanaannya masih kosong.
Jika transisi ini tidak dirancang dengan matang dan disepakati bersama, maka bukan demokrasi mapan yang akan kita panen, melainkan kekacauan administratif dan krisis legitimasi.
Kita tidak bisa membiarkan keputusan besar ini tanpa arah. Mahkamah Konstitusi sudah memberi dasar hukum. Tugas menyusun aturan main selanjutnya ada di tangan DPR dan Pemerintah. Kalau mereka lambat bergerak, kekosongan hukum dan kekacauan teknis akan jadi masalah nyata.
Sebagai masyarakat, kita tidak boleh diam. Yang dipertaruhkan bukan hanya jadwal pemilu, tapi masa depan demokrasi. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.