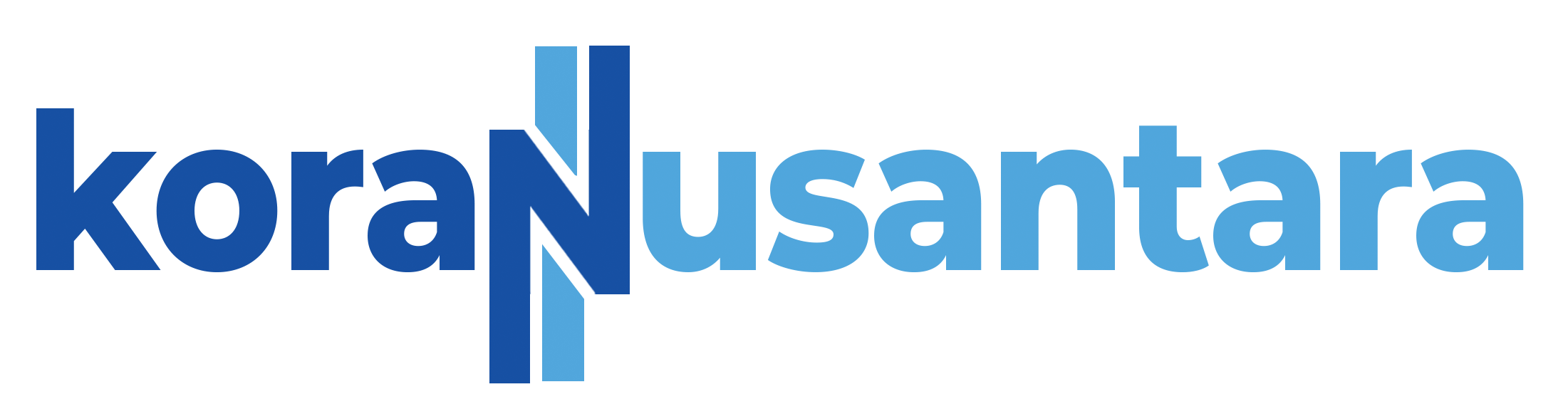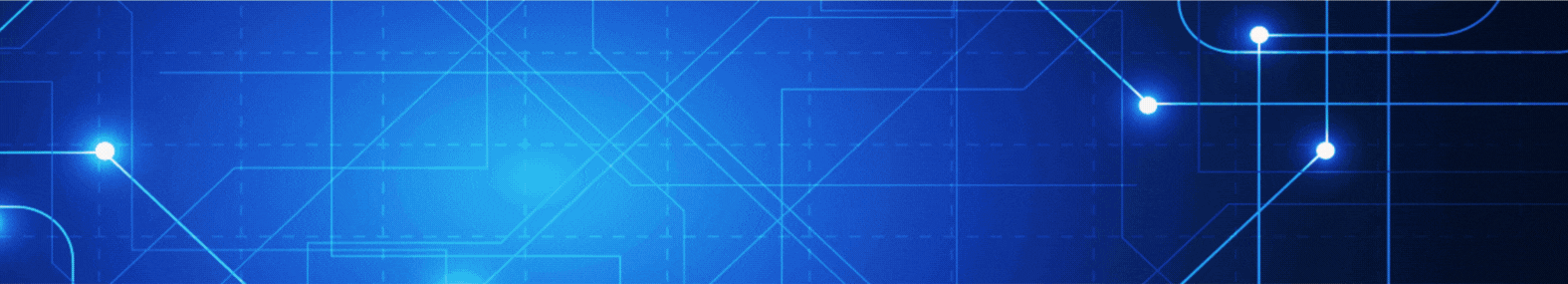SAMARINDA – Rencana revisi sejarah nasional oleh pemerintah mengundang polemik. Di tengah kekhawatiran manipulasi narasi, sejarawan Safardy Bora menegaskan sejarah bukan alat kekuasaan, tapi kesadaran kolektif yang harus dijaga dengan jujur dan objektif.
Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini ditarget rampung pada peringatan 80 tahun kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025. Pemerintah melibatkan sejumlah sejarawan dan arkeolog dengan misi memperkuat identitas nasional dan memperkaya pemahaman generasi muda.
Namun publik mengkhawatirkan lahirnya narasi tunggal yang mengaburkan fakta, khususnya soal pelanggaran HAM dan peran tokoh-tokoh dari luar Jawa.
Menanggapi isu ini, kami mewawancarai Safardy Bora, sejarawan asal Kaltim dan penulis buku Perjuangan Sultan Aji Muhammad Idris di Sulawesi Selatan.
Bagaimana Anda memandang rencana penulisan ulang sejarah Indonesia?
Sebagai penulis sejarah, saya menyambut baik inisiatif seorang menteri yang ingin menulis ulang sejarah Indonesia dengan satu syarat: bahwa hal ini dilakukan bukan demi pencitraan politik, melainkan untuk memperbaiki narasi nasional yang selama ini sering timpang. Sejarah kita terlalu luas untuk dipadatkan dalam satu naskah tunggal. Sejak migrasi Austronesia dari Formosa, lahirnya komunitas Melayu Tua dan Proto, hingga berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai (kerajaan Hindu tertua abad ke-4 M), Sriwijaya, Pajajaran, Majapahit, hingga Islamisasi di Kutai dan Kesultanan lainnya, terlalu banyak fragmen sejarah yang masih tersembunyi di balik “sejarah nasional” yang berpusat di Jawa.
Apa risiko dan potensi manfaat dari penulisan ulang sejarah oleh negara?
Risiko terbesar dari penulisan sejarah oleh negara adalah lahirnya narasi tunggal yang berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kita sudah belajar dari era Orde Baru, ketika sejarah G30S dan peran militer dikisahkan dengan satu sudut pandang. Tetapi penulisan ulang juga bisa memberi manfaat besar: memberi ruang bagi tokoh-tokoh dan peristiwa yang lama dibungkam. Misalnya, sosok Andi Depu, perempuan pejuang dari Mandar yang melawan kolonialisme Belanda, sering luput dari buku teks sejarah nasional. Atau peristiwa kelam yang selama ini hanya dikenal di tingkat lokal: pembantaian sekitar 40.000 warga sipil oleh tentara Belanda dalam operasi militer di Sulawesi Selatan dan Barat (1946–1947) yang dipimpin Westerling.
Prinsip apa yang harus dijaga dalam menulis ulang sejarah?
Prinsip Menulis Sejarah: Objektif, Inklusif, dan Berdasar Fakta
Menulis sejarah, apalagi menulis ulang, memerlukan prinsip ilmiah yang ketat: berdasar bukti, menyertakan beragam perspektif (terutama dari daerah-daerah luar Jawa), dan tidak tunduk pada kepentingan politik sesaat. Sejarah bukan milik penguasa. Ia adalah milik kolektif bangsa. Maka, tokoh seperti Prof. Dr. Susanto Zuhdi, akademisi dari Universitas Indonesia yang dikenal karena pendekatan kritis dan keterbukaannya dalam menelaah sejarah maritim dan Islam di Nusantara, menjadi penting dalam tim penulis ulang. Kehadirannya menjanjikan keseimbangan antara akademik dan narasi publik.
Apakah sejarah memang perlu ditulis ulang?
Secara akademik, sejarah memang perlu ditulis ulang jika:
– Ada temuan baru, seperti bukti arkeologis atau dokumen kolonial yang sebelumnya dirahasiakan.
– Terjadi bias historiografi, seperti dalam narasi “penjajahan Belanda selama 350 tahun”.
Angka 350 tahun ini sendiri problematis. Kutai sudah berdiri sejak abad ke-4, dan Belanda baru efektif menjajah seluruh wilayah Nusantara sekitar abad ke-19. Sebelumnya, dominasi mereka terbatas pada kota-kota pelabuhan di pesisir dan sangat tergantung pada VOC (1602–1799), bukan pemerintah kolonial langsung. Maka, kalimat “Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun” perlu direvisi dengan konteks wilayah dan waktu yang berbeda-beda.
Apakah ada kekhawatiran bahwa penulisan ulang ini akan disalahgunakan?
Tentu. Sejarah bisa jadi alat kekuasaan jika tidak dikawal. Tokoh dari daerah bisa dihapus, sejarah lokal dibungkam, penguasa diglorifikasi. Kita harus kritis, bukan sinis. Jangan biarkan sejarah jadi alat propaganda, tapi sarana refleksi dan penguatan identitas bangsa.
Apakah Indonesia pernah mengalami penulisan ulang sejarah yang mengaburkan fakta?
Jejak Penulisan Ulang yang Menghapus Fakta
Indonesia pernah mengalami sejarah yang “dibersihkan”. Penulisan sejarah resmi di era kolonial hanya mencatat Belanda dan VOC, tanpa menyebut pahlawan lokal kecuali jika melayani narasi kolonial. Era Orde Baru pun menegaskan sejarah yang sentralistik. Akibatnya, tokoh seperti Sultan Hasanuddin, Aru Palaka, hingga kerajaan Luwu atau Ternate terpinggirkan. Bahkan narasi Islamisasi pun direduksi dan dilekatkan hanya pada Jawa atau Sumatra.
Bagaimana menjamin objektivitas dalam penulisan ulang sejarah?
Menjaga Objektivitas Sejarah
Agar penulisan ulang sejarah tetap objektif:
– Harus melibatkan tim lintas disiplin dan daerah.
– Arsip harus terbuka bagi publik.
– Komunitas sejarawan dan jurnalis diberi ruang untuk mengkritisi hasil narasi resmi.
– Sekolah dan kampus tidak hanya mengajarkan hafalan, tetapi juga pemahaman kritis terhadap sejarah.
Seberapa inklusif sejarah yang diajarkan saat ini?
Keberagaman Perspektif dalam Penulisan Sejarah
Penulisan sejarah saat ini memang mulai terbuka. Namun ia masih belum cukup merepresentasikan keragaman Nusantara. Sejarah Mandar, Bugis, Dayak, Minahasa, hingga masyarakat Papua masih minim dalam buku sejarah sekolah. Padahal sejarah Indonesia adalah sejarah bahasa, darah, dan debu dari ratusan pulau dan ribuan komunitas. Maka menuliskan kembali sejarah bukanlah tindakan menyempurnakan satu buku, tetapi memperbaiki fondasi kesadaran kebangsaan.
Apa beda menulis ulang, merevisi, dan memperbarui sejarah?
Menulis Ulang vs Merevisi Sejarah
Perlu dibedakan antara:
– Menulis ulang sejarah: Rekonstruksi menyeluruh, bisa menyentuh narasi besar dan struktur interpretasi sejarah.
– Revisi sejarah: Perbaikan atas detail yang salah atau bias.
– Pembaruan sejarah: Penambahan informasi atau pendekatan baru, misalnya melalui sumber lisan, digitalisasi arsip, atau metode interdisipliner.
Apa peran komunitas sejarawan dan akademisi dalam proses ini?
Tugas akademisi dan sejarawan tidak sekadar menulis di jurnal ilmiah, tetapi menjadi penjaga moral sejarah. Merekalah yang mengawal agar sejarah tetap adil, akurat, dan membumi. Melibatkan masyarakat, mendidik guru, menulis buku sejarah daerah, bahkan menyusun kurikulum SD agar anak-anak tidak hanya menghafal angka penjajahan, tetapi memahami semangat perjuangan itulah tantangan sejarah hari ini.
Safardy menyimpulkan sejarah bukan hafalan, tapi kesadaran. Ia harus diajarkan sejak sekolah dasar bukan sebagai deretan nama dan angka, tapi sebagai refleksi tentang jati diri bangsa. Bahwa kita adalah pewaris Austronesia, pembentuk kerajaan maritim, penerus nilai-nilai Islam dan Hindu-Buddha, korban penjajahan, dan pemilik suara kemerdekaan.
Menulis ulang sejarah bukan membongkar masa lalu, tapi membangun masa depan dengan pijakan yang lebih adil, lebih dalam, dan lebih jujur.
Penulis: Hanafi
Editor: Agus S